Prof. Yusmar Yusuf : Anak Pekan

Maka, perhimpunan dari sejumlah “ruang-ruang kurang ajar” itu lah yang membentuk
komunitas kreatif dan identitas ‘keragaman logis’. Dia boleh dimulai dari tungkai tiang payung peneduh niaga kulak, kemudian disapa dalam candaan alegoris; Payung Sekaki. Boleh juga diawali pokok rindang teduh-teduh, tempat orang berniaga rempah-rempah; pokok kayu lebat-rindang itulah Sena (angsana): Senapelan.
“Ruang kurang ajar” berikutnya? Dia telah menjadi sebuah perhimpunan rutin empat kali dalam satu purnama, lalu disebut Pekan. Pekan atau polis; sebuah upaya dari “ruang-ruang kurang ajar” itu mendikte zaman dalam sejumlah ‘desakan’ untuk memulia ‘keragaman logis’, oleh Montesquieu ditabal dengan sapaan
esprit g ̀n ̀ral.
Di atas dada Pekan, berlangsung perjumpaan “keriangan benua dan keriangan maritim”. Di awal pembentukan Pekan sebagai “ruang kurang ajar” itu, dia berpembawaan a-tempo (tanpa waktu), lalu digelombangi oleh waktu kini dan nanti (co-tempo). Sejak itu terbentang garis
pembatas “imajinatif” tentang waktu (tempo): Pekan Lama dan Pekan yang Baru. Pekan yang baru ini menjelma dalam gelinjang serba tak terduga, karena dikenderai oleh sehimpunan “keragaman logis”, lalu dia bersalin menjadi Neopolis, New Poli, kemudian disapa secara glamour menjadi Napoli (ya, di Italia sana, dalam fenomena kelasakan maritim kekaisaran Romawi).
Pekanbaru atau Pekan Baharu tampil dalam cahaya Napoli, tapi di hulu sungai. Dia lebih
bersuasana New Orleans yang menempel di punggung Mississippi . New Orleans, sejatinya memang dilekatkan dengan gelar “kota kurang ajar”. Di sini kaum-puak Negrito yang melawan dan mengandang arus dominasi kulit putih berlangsung dalam rempak tone (nada), kecipas kaki dan gerak kamulflase dalam sejumlah hidangan bebunyi yang ranggi, falsetto, tak beraturan, menghidang ‘kemiripan misteri’, menggemukkan segala bunyi makhluk yang berdaya apung “mencemeeh dan mengejek” orang-orang putih.
Namun, si putih tak merasa diejek atau dicemeeh, mereka malah tertikam oleh ekstase kenikmati bebunyi yang dilaung oleh komunitas hitam sepanjang jalan, di celah lorong, ujung pelabuhan dan pangkal pokok kayu merimbun. Di kota ini tempat lahirnya Jazz yang mengusung “rukun iman” baru dalam bahasa musik: “musica franca”. Jazz menjadi rose-nya musik dunia, mengganti posisi singgasana musik Klasik dan Barock sebelumnya yang muai di tanah Eropa.
Kota “kurang ajar” berikutnya New York, di sini ada Broadway. Kota jenis ini pula yang
melahirkan para jenius; John Coltrane, Carl E. Sagan, Abraham Maslow. Kota-kota yang bergemuruh selalu diawali dari sebuah metamorfose serba berdebu dan sejumlah arkian, amsal dan ibarat.
Dalam maung-hapak amsal dan ibarat itulah terjuntai “ruang-ruang bid’ah” yang diidamkan untuk sebuah fermentasi kebudayaan. Ruang-ruang “bid’ah”, bolehlah disetarakan dengan “ruang-ruang kurang ajar” yang menghasilkan ‘sekuntum mawar’ dari proses stilasi (penyulingan murni) sebuah kehendak esprit g ̀n ̀ral itu. Maka, jadilah fenomena “Anak Pekan” dalam langgam anak metropolitan sungai-sungai sebagaimana Paris, Seoul, Frankfurt, London, Budapest, Bratislava, Kairo, Basra, Kuala Lumpur, Bangkok.
Anak Pekan, tak harus Melayu. Dia adalah hasil dari stilasi (sulingan) dari “keragaman logis”
yang dirindukan. Dia lahir dari sebuah gairah ‘memberi’. Ya, kota yang ‘memberi’. Bukan kota yang “mengambil’.
Saya lahir di kampung, bukan anak Pekan. Syamsuar yang Gubernur itu anak kampung, bukan anak Pekan, Firdaus juga anak Ocu, bukan anak Pekan. Tapi anak keturunan saya,anak Syamsuar dan Firdaus itu adalah anak Pekan.
Mereka membangun semacam ‘new proud’
(kebanggaan dan keriangan baru) selaku anak Pekanbaru yang hidup dalam julangan keriangan
“keragaman logis”. Dia bukan entitas kebangsaan (nationalitas); tetapi lebih kepada ‘rasa cinta’ dan ‘gairah wathan’, bukan pula ‘gairah bani’ (turunan dzuriat). Aras berfikir Anak Pekan, mengatasi
ruang Andalas.
Mereka melekatkan diri selaku makhluk antar benua (inter continent); chillout, hangout dan kongkow dalam ruang-ruang binar berkapasitas identitas historis menganga. Alias, mereka adalah kaum terbuka dan membuka diri; baik angin yang datang dari timur laut, tenggara, barat laut, maupun barat daya. Mereka tak mempertengkarkan mata angin standar:Timur, Barat, Utara dan Selatan.
Mereka boleh Cina, Batak, Minang, Melayu, Jawa, Bugis, Banjar dan bahkan mixed-creol, tapi dipersatukan oleh loghat bicara dalam ujung lunak (penegas); serba “dooo” atau “doowww”: “Tidak doo”. “Tak apa-apa doow...” Mereka membentuk kota ini menjadi kota yang “memberi”. Namun, kita yang tua-tua ini masih terjebak membangun kota ini sebagai kota yang ‘mengambil’ dan ‘meminta’. Cara ‘mengambil’ dan ‘meminta’ itu? Menuduh bahwa banjir kota disebabkan oleh sungai yang mendangkal. Sungai mendangkal karena ada penambangan pasir liar.
Geo-morfologi sungai-sungai yang melintasi kota ini cermati dulu. Jangan main tuduh haiiii wahaiii..
Anak-anak Pekan ‘memberi’ kita acuan ‘milenial nomies’ yang membaharu (co-tempo); tak
dihalang oleh partisi ruang kerja, dinamis, menguasai bahasa coding- digitalized, tapi kita
membajaknya menjadi milenial ‘rasa istana’. Yang ditangkap hanya tampilan permukaan
(superficial); gaya tampil, sneakers, busana casual, kenderaan custome, maksa seolah-olah club hobby vespa, motor gede dan seterusnya.
Anak-anak Pekan yang Neopoli itu ‘memberi’ kita resam hidup serba kreatif, lalu kita meringkusnya menjadi sesuatu yang “terlembaga” (Badan Kreatif); kuliner kreatif (ha?) yang dimotori ibu-ibu penguasa. Dekranasda sebagai tempat berhimpunnya para perajin (yang idem ditto kreatif) itu, juga dibonsai menjadi lembaga semi-birokrasi versi kaum emak-emak penguasa.
Sekali lagi, anak-anak Pekan yang kreatif itu ditelikungi di persimpangan kuasa-politik seakan simpangan carrefour.Walhasil? Mereka tampil manyun mencemeeh kita, untung dibungkus masker hari-hari ini.
Anak-anak Pekan yang lasak ini senantiasa membangun sejumlah suak-suak elakan serba cergas sepanjang “ruang-ruang kurang ajar” yang serba baru dan progresif. Mungkin tersebab kedunguan dan kebekuan kita selalu ‘mengambil’ dan ‘meminta’ itulah yang menjadi motor penggerak mereka bersetia membangun “ruang-ruang kurang ajar” yang baru dan progresif.
Beberapa nama anak Pekan yang menggoda selebral kita: Dedi Ariandi, Parlin, Bens Sani, Fedli, Mita, Farradinna dan segerombolan anak Pekan lintas suku yang tak dikangkangi tanjak, pun senantiasa mentertawai
“bani tugu” Ha ha ha ...

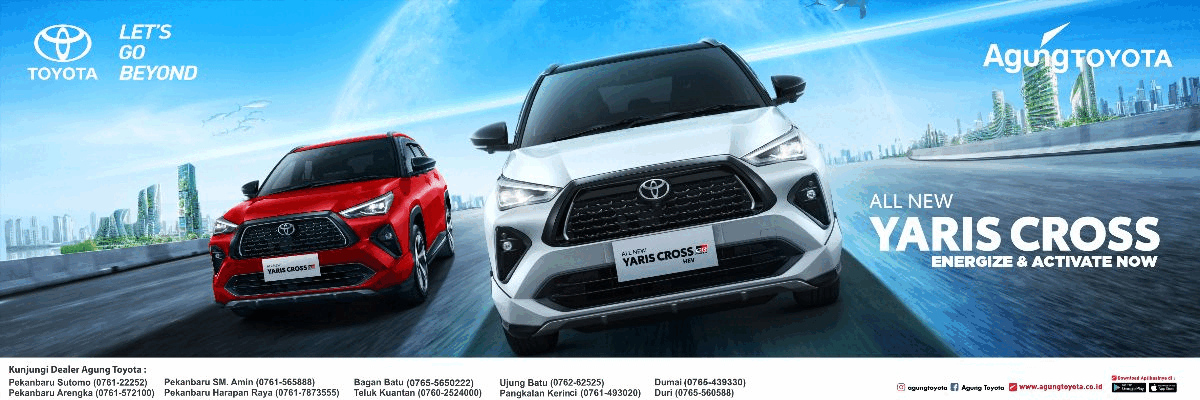



Tulis Komentar